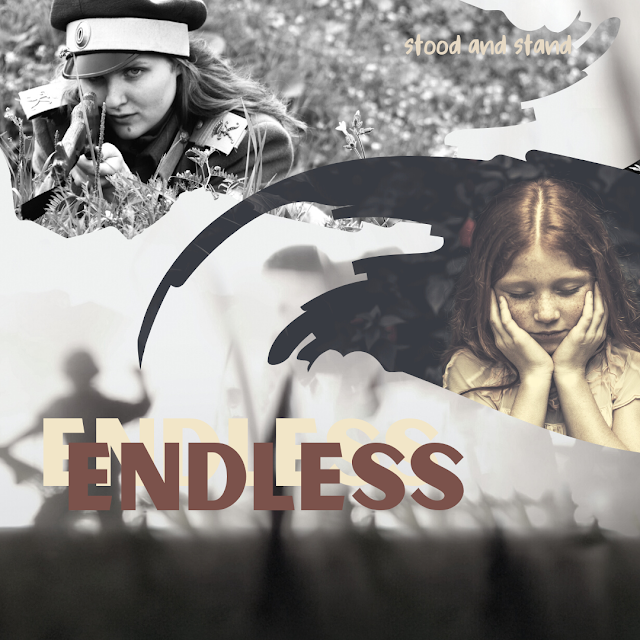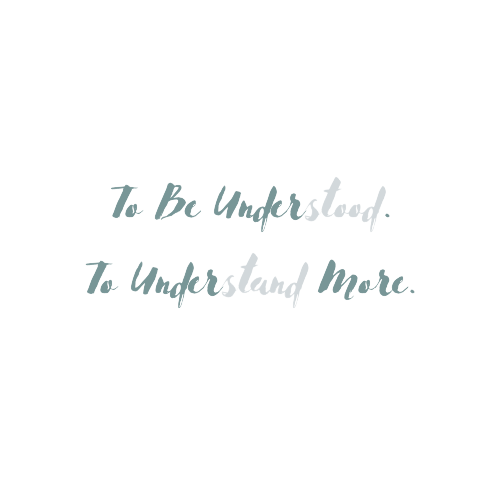Berdiri
di sini, di daerah ini, kulihat Gamal berada di setiap batas tepi. Tak
kuketahui pasti siapa yang menanamnya di sana, tetapi ia telah ada semenjak
pertama kali kumenyadari keberadaanku di bumi ini. Mereka bilang adanya Gamal
membuat segala yang kujalani menjadi aman terkendali. “Aman terkendali, apakah
makhluk di luar sana sebegitu ganasnya?”, pertanyaanku pada mereka. Jawaban
yang dilontarkan kurasa tak menjawab pertanyaanku, “Memang kamu seharusnya di
sini, bukan di luar sana.” Apakah Tuhan memberiku identitas tentang ‘seharusnya
di sini’? Aneh.
Keinginanku untuk mencari tahu membawaku mencari celah di
antara para Gamal itu. “Tak ada yang beda”, kataku dalam hati. Pun, aku tak
menemukan sesuatu yang membuatku merasa ‘seharusnya di sana’. Berselang 10
menit, kurasa aku harus menarik perkataanku tadi, perang ada dimana-mana.
Sungguh, tapi apakah perang seperti ini
hanya terjadi pada kaumku? Jantungku terasa sedang berlari di tempat, perkataan
dan perbuatan itu, “Terbungkus sekali, harusnya dirimu kubungkus dengan hal
lain, Mbak.”, tak tahu aku harus bagaimana. Kucoba untuk mengalihkan pandangan,
justru kedua mata ini melihat perang lain. Di sini tak ada Gamal yang memberi
batas tepi, tetapi kenapa semua seolah tak ada yang memberi kebebasan pasti?
Berlari, terus berlari ke dalam kawasan Gamal tempatku
berasal. Semua melebarkan sudut matanya, amarah keluar dari masing-masing
mereka. “Kau sudah kuberi tahu, tak seharusnya kau di sana.” Kenapa tak ada
rasa khawatir yang diberikan padaku, kenapa justru omelan itu? “Apakah tak ada
kebebasan untukku melakukan hal yang kumau?”, tanyaku. Mereka menjawab bahwa
aku bebas melakukan apa yang kumau asal tak keluar dari batas Gamal itu, bahwa
inilah ruang amanku. Aneh, sungguh mengekang.
Bukankah manusia harusnya memperlakukan manusia lain
seperti ‘selayaknya manusia’? Bukankah tanpa Gamal pun, harusnya seluruh bumi
tempat kaki dipijakkan ini adalah ruang aman bagi manusia, bagi kaumku, bagi
perempuan? Konsep aneh, mengapa ruang aman harus membatasi dan mengekang.
Harusnya ‘Gamal’ itu berada pada pilihanku, bukan standar yang mereka tetapkan
sebagai ‘seharusnya’. Harusnya kesadaran memperlakukan ‘selayaknya manusia’
kokoh menetap pada diri semua manusia. Namun, apakah seharusnya aku mengganti
nama menjadi ‘Gamala’? Agar batasan ruang aman tempatku melakukan hal yang
kumau adalah pilihanku sendiri?
Tulisan ini juga termuat dalam virtual exhibition Aksara Bersuara Girl Up Universitas Gadjah Mada: Menciptakan Ruang Aman bagi Korban Kekerasan Seksual melalui Aksara